Desa, Kebudayaan, dan Kearifan Lokal di Tengah Arus Perubahan
Oleh Redaksi Lintasdesa.com.
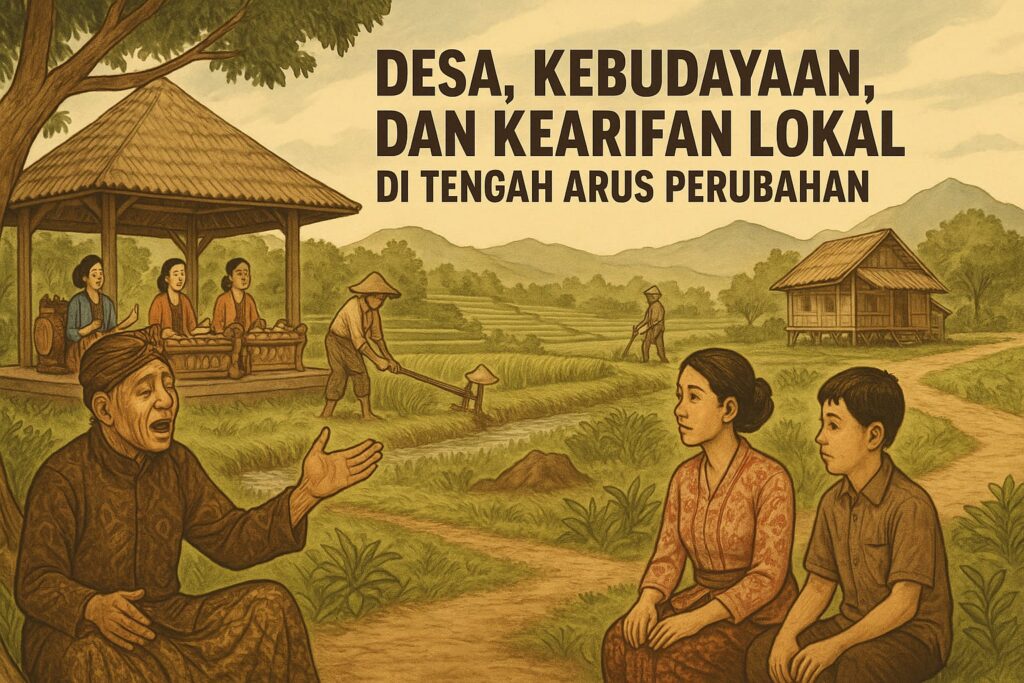
Di sudut selatan Gunung Tambora, seorang tetua adat memandangi sawah yang mulai kering. Musim hujan yang datang tak menentu membuat warga desa kehilangan irama tanam yang biasa mereka warisi dari nenek moyang.
Sistem tanam tana co’i, yang selama ratusan tahun terbukti tangguh menghadapi iklim, kini kerap disingkirkan karena dianggap “tidak modern”. Padahal di balik pola tanam itu tersimpan kearifan lokal yang sudah terbukti selaras dengan siklus alam tropis.
Pemandangan seperti itu bukanlah anomali. Di banyak pelosok Indonesia, budaya dan pengetahuan lokal terdesak oleh arus perubahan yang datang begitu cepat. Globalisasi dan pembangunan teknokratis menyapu desa-desa dengan kecepatan yang tidak selalu ramah terhadap nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun.
Namun desa bukan sekadar ruang geografis. Ia adalah denyut hidup, tempat budaya bernapas, dan di sanalah akar bangsa ini bertumbuh.
Selama satu dekade terakhir, desa mengalami transformasi besar. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, desa memperoleh legitimasi politik, kewenangan otonom, dan dana pembangunan yang signifikan. Dana Desa yang mencapai triliunan rupiah setiap tahun membuka banyak peluang. Infrastruktur tumbuh, jalan dibangun, balai desa direhabilitasi.
Namun dalam derasnya arus pembangunan fisik dan ekonomi, budaya kerap tertinggal di belakang. Seni lokal tak lagi diajarkan, upacara adat dikurangi, dan ruang budaya bergeser menjadi seremonial belaka. Dalam banyak Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), istilah “kebudayaan” seringkali muncul sebagai pelengkap tanpa arah kebijakan yang jelas.
Padahal justru dalam budaya lokal tersimpan jawaban atas banyak persoalan hari ini: krisis identitas, disorientasi moral, bahkan kerusakan lingkungan. Masyarakat adat di Kalimantan Tengah, misalnya, memiliki sistem larangan merambah hutan di waktu-waktu tertentu. Di Bali, filosofi Tri Hita Karana menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan dalam semua lini kehidupan.

Kearifan seperti itu bukan mitos atau romantisme masa lalu. Ia nyata, hidup, dan relevan untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.
Arah angin kini mulai berubah. Dalam kebijakan terbaru pemerintah pusat, budaya desa mulai mendapatkan ruang yang lebih tegas. Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 menetapkan bahwa penggunaan Dana Desa 2025 harus menyentuh sektor-sektor strategis seperti ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, dan pelestarian kearifan lokal.
Selanjutnya, Kepmendesa Nomor 3 Tahun 2025 mengarahkan desa untuk memperkuat kelembagaan adat serta menggunakan pendekatan berbasis budaya dalam pengembangan desa wisata, ekonomi kreatif, hingga mitigasi bencana.
Beberapa daerah juga sudah lebih progresif. Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan memberi perlindungan hukum atas wilayahnya. Di Kalimantan Selatan, pemerintah provinsi telah mengesahkan Perda Desa Wisata dan Kearifan Lokal, memberikan dasar hukum untuk mengembangkan pariwisata budaya yang berpihak pada warga.
Namun implementasi belum seindah rumus di atas kertas. Banyak kepala desa belum memahami bagaimana menerjemahkan nilai budaya menjadi program pembangunan. Di sisi lain, minimnya dokumentasi dan literasi budaya membuat banyak warisan lokal tidak dikenali oleh generasi muda. Di sinilah tantangan terbesar kita hari ini: bagaimana menjembatani tradisi dan modernitas tanpa saling mengorbankan.
Kebudayaan tidak akan bertahan hanya dengan romantisme. Ia butuh sistem. Ia butuh kebijakan yang berpihak, anggaran yang konkret, dan pelibatan masyarakat secara bermakna.
Desa perlu diberi ruang untuk memimpin pelestarian budaya mereka sendiri, bukan sebagai obyek proyek, tetapi sebagai subyek kebudayaan yang berdaulat. Pemerintah pusat dan daerah harus menyediakan pelatihan dan pendampingan teknis bagi aparat desa untuk mengenali, mengelola, dan menghidupkan kembali kearifan lokal sebagai bagian dari strategi pembangunan desa.
Lebih dari itu, lembaga pendidikan dan media lokal juga harus turun tangan. Kurikulum sekolah dasar bisa memasukkan dongeng, lagu daerah, dan permainan tradisional sebagai bagian dari proses belajar. Televisi dan media daring harus memberi tempat bagi kisah-kisah desa, bukan hanya narasi urban yang mendominasi ruang publik.
Dan yang tak kalah penting: anak-anak muda desa. Mereka bukan hanya pengguna TikTok atau penonton YouTube. Mereka pewaris nilai, penjaga batas, dan pemilik masa depan. Jika mereka tidak mengenali akar mereka, maka tak ada lagi tempat budaya berpijak di generasi mendatang.
Pembangunan desa yang abai terhadap kebudayaan dan kearifan lokal ibarat membangun rumah tanpa pondasi. Megah di permukaan, tapi rapuh di dalam. Ketika pembangunan hanya dilihat dari sisi fisik dan ekonomi, maka yang terjadi adalah pertumbuhan tanpa jiwa—sebuah kemajuan yang mencabut desa dari sejarah, identitas, dan makna hidup kolektifnya.
Jika kita terus mengabaikan pembangunan berbasis kebudayaan, maka akan lahir generasi yang terasing dari tanahnya sendiri. Bahasa daerah menghilang, tradisi ditinggalkan, dan nilai-nilai luhur yang selama ini menjadi penyangga harmoni sosial digantikan oleh logika pasar semata. Konflik agraria, krisis ekologi, hingga keretakan sosial semakin sulit diurai karena akar penyelesaiannya—yakni kearifan lokal—telah ditinggalkan.
Lebih jauh lagi, hilangnya budaya lokal berarti hilangnya sumber inovasi dan daya tahan masyarakat dalam menghadapi krisis. Di tengah perubahan iklim, krisis pangan, dan ketidakpastian global, desa yang kuat adalah desa yang berpijak pada pengetahuan lokal, solidaritas sosial, dan filosofi hidup yang selaras dengan alam. Tanpa itu, desa akan mudah rapuh meski tampak maju dari luar.
Sudah saatnya arah pembangunan berbalik: bukan sekadar membawa desa menuju kota, tetapi menghadirkan kekuatan desa sebagai inspirasi peradaban. Karena hanya dengan menjadikan budaya dan kearifan lokal sebagai poros, kita bisa membangun desa yang bukan hanya hidup, tapi juga menghidupkan masa depan.



